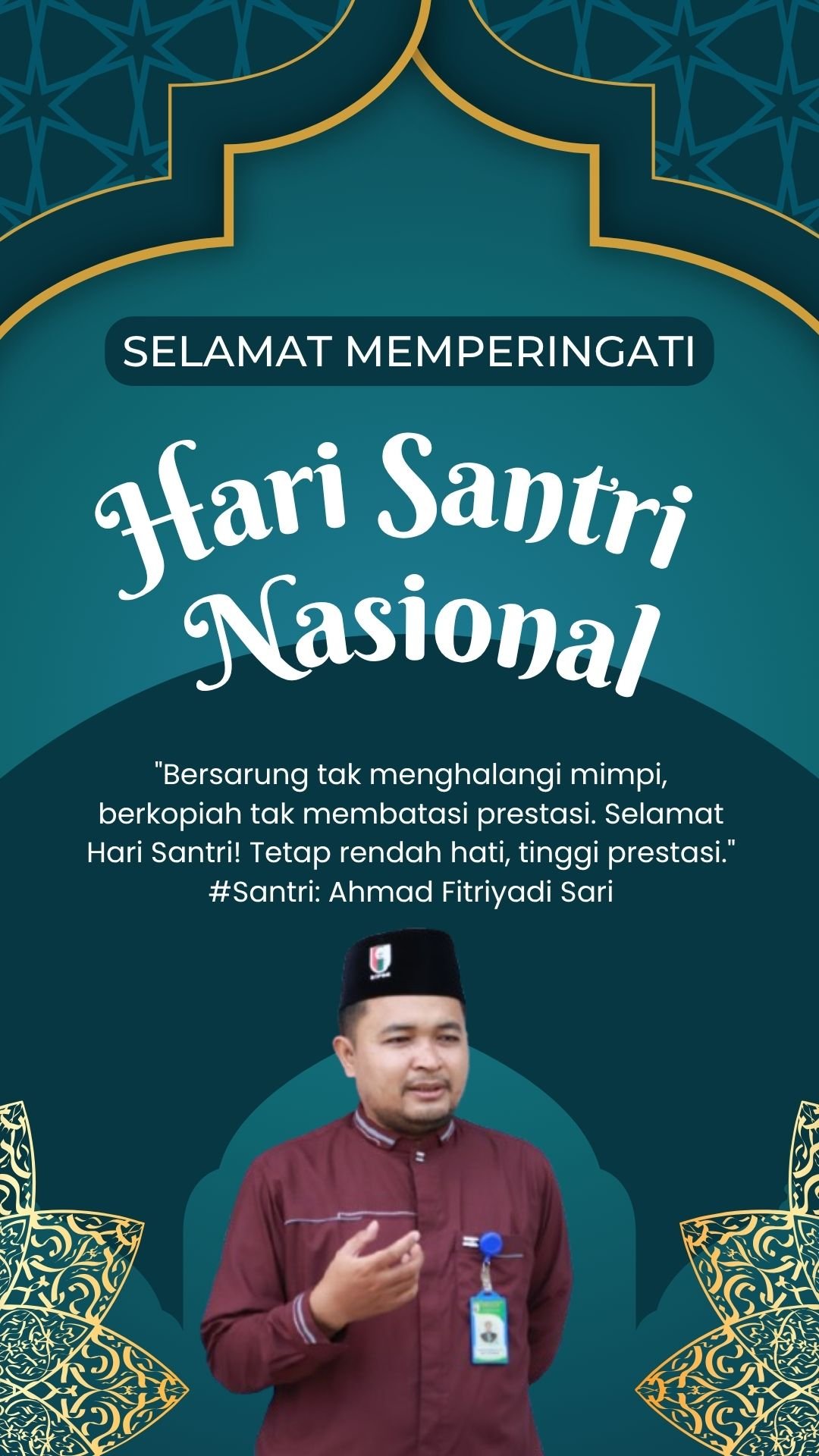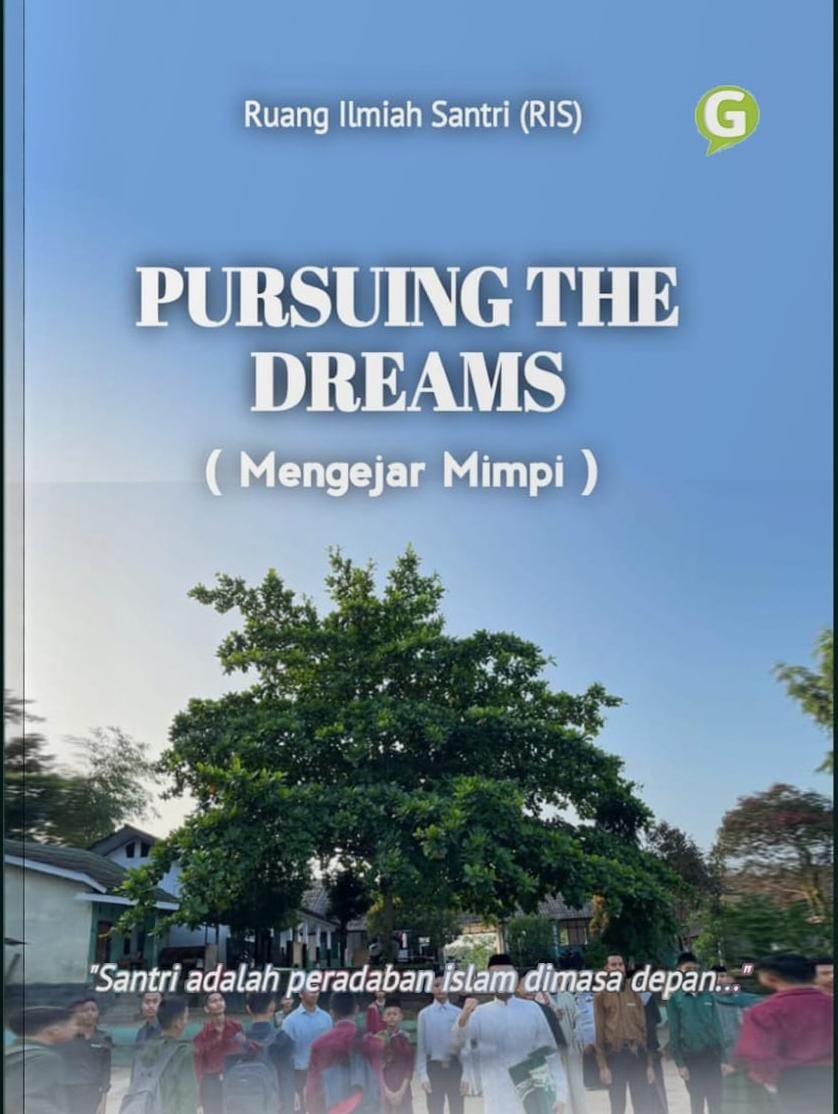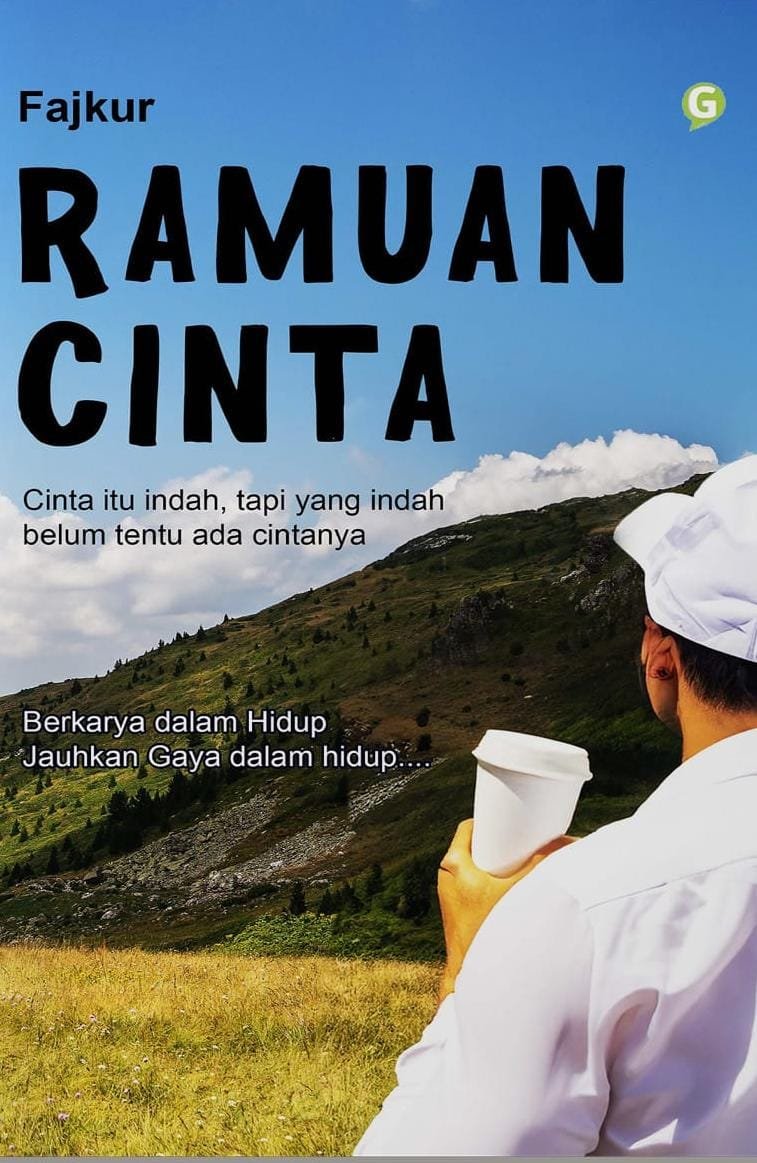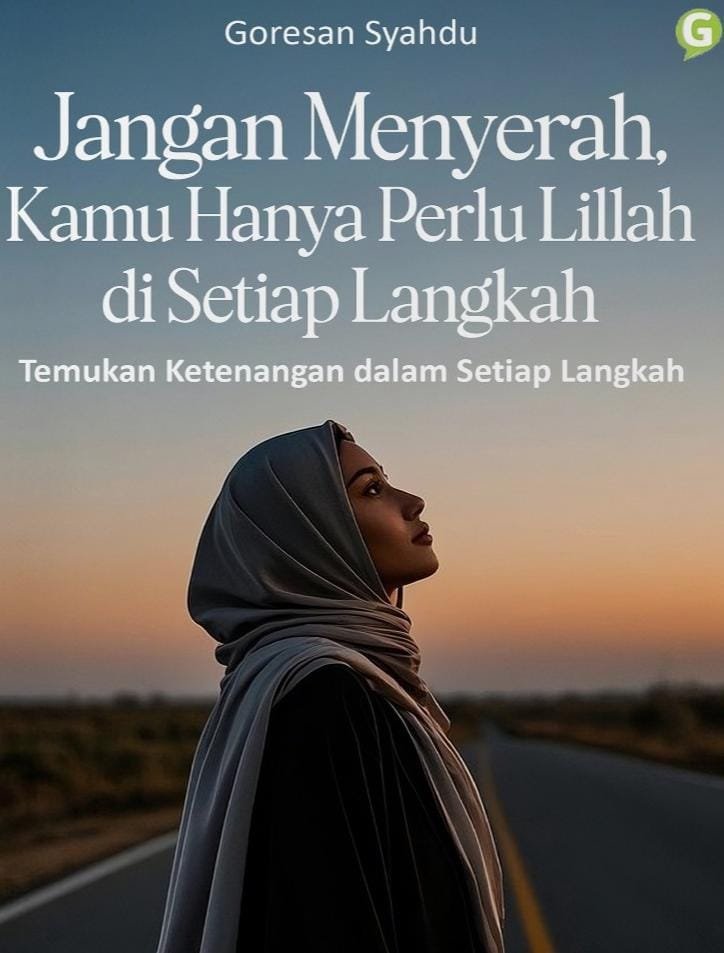Oleh: Ahmad Fitriyadi Sari
Pendahuluan
Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penetapan Hari Santri didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Peringatan ini bukan hanya momentum seremonial, melainkan refleksi atas kontribusi besar kalangan pesantren dalam membangun karakter bangsa yang religius, cinta tanah air, dan berakhlak mulia. Dalam konteks sejarah, Hari Santri memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa bersejarah ‘Resolusi Jihad’ yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang kemudian menjadi salah satu pemicu pertempuran 10 November di Surabaya.
Sejarah dan Latar Belakang Hari Santri
Sejarah Hari Santri berawal dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pasca-proklamasi. Ketika pasukan Sekutu datang ke Indonesia bersama tentara Belanda (NICA) dengan dalih melucuti senjata Jepang, mereka justru berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial. Dalam situasi genting itu, KH. Hasyim Asy’ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Resolusi tersebut menyerukan kewajiban bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut berbunyi bahwa ‘berjuang melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa di Indonesia hukumnya fardhu ain bagi setiap Muslim’. Seruan itu membakar semangat rakyat, terutama kalangan santri dan pejuang, untuk melawan penjajah. Dalam perspektif sejarah, Resolusi Jihad menjadi bukti nyata keterlibatan pesantren dan santri dalam perjuangan nasional.
Makna Filosofis dan Ideologis Hari Santri
Secara filosofis, Hari Santri mengandung nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, dan moralitas. Santri dipandang sebagai sosok yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Dalam ajaran Islam, cinta tanah air (‘hubbul wathan minal iman’) menjadi bagian dari iman, dan hal ini tercermin dalam perjuangan para santri yang menempatkan kemerdekaan sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama. Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki karakter khas yakni kemandirian, kebersahajaan, dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, Hari Santri bukan sekadar peringatan historis, tetapi juga momentum memperkuat karakter bangsa berbasis nilai-nilai pesantren.
Kontribusi Santri dalam Perjuangan dan Pembangunan Bangsa
Kontribusi santri tidak hanya terbatas pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Dalam bidang pendidikan, pesantren telah berperan mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia. Dalam bidang sosial, santri turut menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Dalam bidang politik, banyak tokoh nasional lahir dari lingkungan pesantren, seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ma’ruf Amin, dan KH. Hasyim Muzadi. Selain itu, pesantren kini berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan koperasi, kewirausahaan, dan inovasi digital.
Relevansi Hari Santri di Era Modern
Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, nilai-nilai santri tetap relevan dan bahkan semakin penting. Santri modern dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai spiritual. Konsep ‘Santripreneur’ yang digagas Kementerian Agama merupakan salah satu upaya memadukan semangat kewirausahaan dengan etika pesantren. Santri diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi sosial, ekonomi, dan moral di tengah tantangan global. Menurut Menteri Agama (2023), Hari Santri menjadi pengingat bahwa semangat keislaman dan kebangsaan tidak boleh dipisahkan, karena keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
Nilai-nilai Pendidikan yang Dapat Diambil dari Hari Santri
Dari peringatan Hari Santri, terdapat sejumlah nilai pendidikan yang dapat diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, nilai keikhlasan, yaitu semangat berjuang tanpa pamrih sebagaimana dicontohkan para santri. Kedua, nilai disiplin dan kemandirian, karena kehidupan di pesantren membentuk karakter tangguh dan mandiri. Ketiga, nilai nasionalisme religius, yaitu keseimbangan antara cinta tanah air dan ketaatan kepada Tuhan. Keempat, nilai toleransi dan moderasi beragama yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan bangsa yang majemuk. Pendidikan karakter berbasis pesantren ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penutup
Hari Santri Nasional merupakan momentum penting untuk mengenang jasa para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, peringatan ini juga menjadi sarana refleksi bagi generasi muda agar terus meneladani semangat perjuangan, keikhlasan, dan nasionalisme yang diwariskan para santri. Dalam konteks kekinian, santri dituntut untuk mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, Hari Santri tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga komitmen untuk masa depan Indonesia yang berkeadaban, beriman, dan berkemajuan.
Daftar Pustaka
– Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional.
– Abdurrahman Wahid. (1987). Pesantren Sebagai Subkultur. Jakarta: LP3ES.
– Menteri Agama. (2023). Pidato Peringatan Hari Santri Nasional. Kementerian Agama RI.
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
– Zamakhsyari Dhofier. (1994). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES.